Keterasingan Camus
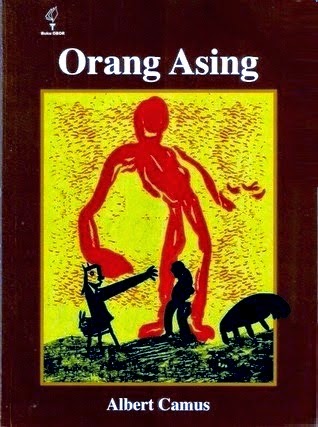 |
| Sumber Gambar |
Albert Camus hidup ketika eksistensi
manusia ditentukan eksistensi manusia yang lain. Kecamuk perang dalam proses
pertumbuhannya serta bentuk penegakan kuasa manusia melalui aturan. Ia juga salah
satu rujukan ketika kita hendak melacak filsafat eksistensialisme, selain
Sartre tentunya. Keduanya memang sahabat. Sartre, misalnya, menulis esai
mendalam mengenang kematian karibnya itu yang harus mangkat karena sebab suatu
sebab. Bukan karena usia sebagaimana lazimnya manusia tahu kalau malaikat
pencabut nyawa telah datang. Camus tewas dalam sebuah kecelakaan mobil di
Villeblevin 5 Januari 1960 di usianya ke 46 tahun.
Di 54 tahun kematiannya, saya baru
membaca novel pertamanya, Orang Asing, usianya baru 29 tahun kala
karyanya ini terbit di tahun 1942. Empat tahun lebih tua dari usia negeri ini
yang baru diproklamirkan di tahun 1945. Dan, saya baru lahir 42 tahun kemudian.
Tepat hari ini, 23 Juni 2014, saya memulai catatan pembacaan ini ketika tim nasional
Aljazair menekuk Korea Selatan 4-2 di penyisihan grup H piala dunia dini hari
tadi.
Camus dan Aljazair, adalah satu
manusia dan tanah kelahiran. 7 November 1913, ia lahir di Mondovi, sekarang
daerah itu bernama Deraan. Novelnya ini pun berlatar belakang kehidupan di
Aljazair, negeri yang pernah dijajah Prancis di mana Camus kemudian hidup
merdeka berpikir di negeri borjuis itu.
“Hari ini Ibu meninggal.
Atau, mungkin kemarin, aku tidak tahu. Aku menerima telegram dari panti Wreda:
“Ibu meninggal. Dimakamkan besok. Ikut berduka cita.” Kata-kata itu tidak
jelas. Mungkin Ibu meninggal kemarin. Begitulah
novel tipis ini dibuka.
Isi telegram itulah yang menjadi peta
perjalanan Meursault menumpangi bis menuju rumah jompo di Marenggo menjumpai
mayat ibunya yang di usia senjanya hidup bergaul sesama lansia.
Meursault, seorang lelaki belum
berkeluarga dan bekerja di sebuah perusahaan. Ia mengambil cuti dua hari
sebagai bentuk peluangan waktu. Sesampai di panti Wreda, ia tak langsung
mendesak pegawai di sana untuk segera menunjukkan tubuh ibunya. Entah apa yang
ada di benak Meursault. Nyatanya lagi, ia tidak menangis atas kehilangan itu.
Walau novel ini didasari sebuah latar
keluarga, Camus tidak menceritakan konflik dalam keluarga itu. Menyangkut ibu
Meursault, misalnya, kita hanya peroleh info sedikit mengenai keberadaannya di
panti jompo. Tokoh-tokoh yang hadir dalam novel ini pun diceritakan
sendiri-sendiri. Ada Marie, pacar Meursault yang juga tidak diketahui dari mana
asalnya serta latar keluarganya. Jangan lupakan Salamano, orang tua yang sibuk
dengan Anjing kudis piaraannya. Yang ada, kita membaca kisah masing-masing tokoh
itu dalam menjalani kehidupannya.
Setelah pemakaman ibunya, Meursault
adalah orang biasa yang tak memiliki musuh. Ia hanya berkutat dengan
kehidupannya sendiri. Tetapi, sebagai tetangga dalam satu apartemen dengan
Raymond Sintes, konflik eksternal meghampirinya juga. Meski begitu, ia masih
memberikan saran kepada Raymond agar tidak memulai kekerasan ketika dirinya dan
Raymond dan juga Masson kala berjumpa dengan rombongan orang Arab. Salah satu
di antaranya merupakan musuh Raymond.
Keakraban itu bermula ketika Meursault
menerima tawaran Raymond makan di kamarnya. Dari sanalah Meursault mengetehui
dari pengakuan Raymond sendiri. Ia telah berkelahi dengan seorang lelaki, yang
mana orang tersebut saudara perempuan yang dijadikan gendak (perempuan
peliharaaan tanpa status pernikahan) oleh Raymond.
Maksud Raymond mengajak Meursault,
ialah untuk meminta nasihat darinya atas masalah yang tengah dihadapinya,
Raymond sadar dengan apa yang selama ini dilakukan. Memelihara perempuan Arab
selaku gundik dan telah diketahui oleh keluarga si perempuan, sunggulah sumber
malapetaka bila tidak mampu mengelolanya.
Namun, Meursault tidak tahu apa-apa,
ia bingung harus memberikan pandangan apa atas masalah yang dihadapi
tetangganya itu. Ia terasing dengan semuanya.
Naas bagi Meursault, justru dari
tangannya seorang Arab musuh Raymond harus mati. Antara sadar dan tidak, pistol
milik Raymond memuntahkan peluru. “…Pelatuk
tertekan, aku menyentuh bagian tengah gagang pistol yang licin, dan saat
itulah, dalam suara yang sekaligus kering, semua itu dimulai…” Begitula
pengakuan Meursault.
Jadilah Meursault melakoni hidupnya di
dunia pengasingan, penjara. Benar-benar asing, sepertinya ia tak begitu
meyakini kalau dirinya telah menghentikan jalan hidup orang lain. Mendahului malaikat
pencabut nyawa. Itu bukan takdir, melainkan nasib tragis antara Meursault dan
orang Arab itu.
Camus, telah meneror pembacanya, saya
merasakannya. Cerita dibuka dengan kematian, puncak nasib yang dialami sang
tokoh utama menjadi sebab dari kematian seseorang. Lalu, tokoh itu pun harus
lekas mati atas kesepakatan dan pertimbangan aturan buatan manusia di dunia.
Meursault ditimpali hukuman mati. Bisakah itu diterima, membunuh karena tidak
sengaja, katakanlah demikian. Tetapi, hukum positif sudah cukup bila bukti
material sudah lengkap.
Anggaplah Meursault tengah berdiri di
tempat yang keliru di mana seharusnya ia tidak di sana. Bukan karena sial,
hanya hukum mati itu perlu penegasan atas tuntutan keadilan. Namun, bisakah hal
ini diterima. Ah! Meursault sendiri bingung. Tepatnya tidak memahami semua yang
telah terjadi. Ia terasing atas apa yang telah dilakukannya sendiri.
Camus tak hanya meneror kita, ia
tengah meghamparkan keterasingan itu sendiri. Umpanya, kita berada di posisi
Meursault, tetapi kita memiliki kesadaran bahwa semua itu bukan atas keinginan
sendiri. Apa yang terjadi hanyalah refleks dari naluri dasar untuk
mempertahankan diri. Perlu bantuan penjelasan lain memang, sayangya, pengakuan
kepala panti Wreda yang dipinta pengadilan untuk memberikan keterangan lain
mengenai siapa itu Meursault. Semakin meyakinkan pihak pengadil kalau si
terdakwa mengidap sesuatu. Ketidakwarasan, karena ia tidak menangisi kematian
ibunya. Suatu hal yang sungguh ganjil. Koruptor sekalipun mungkin akan meratap
bila sang ibunya wafat.
Bagi Meursault, pengadilan tidak
berhak mencapnya berdosa, hanya punya kuasa menetapkannya bersalah atas
peristiwa yang menghilangkan nyawa orang lain. Boleh jadi, sebab itulah ia
menolak kedatangan pendeta untuk menguatkannya menjalani proses hukuman mati.
Tepat pendapat orang lain, pembaca
sebelum saya. Bahwa Camus tak sekadar menulis novel, ia telah menulis traktat
filsafat yang kemudian kita kenal absurditas.
“Apa peduliku pada
kematian orang lain, cinta seorang ibu, apa peduliku pada Tuhan, hidup yang
dipilih orang, nasib yang digariskan, karena hanya sebuah nasib yang harus
memilih diriku sendiri dan bersamaku berjuta-juta orang, dan beberapa orang
yang mempunyai hak istimewa, yang seperti dia, menyebut dirinya, saudaraku.
Mengertikah dia? Betulkah dia mengerti? Semua orang mempunyai hak istimewa.
Yang ada hanya yang mempunyai hak istimewa. Mereka juga akan dihukum pada suatu
hari. Dia juga akan dihukum. Apa peduliku, bila karena dituduh membunuh ia
dihukum mati, karena tidak menangis pada waktu penguburan ibunya…”
Petikan di atas adalah teriakan
Meursault di hadapan pendeta yang coba menasihatinya. Teranglah, tokoh
Meursault tak lain merupakan suara Camus sendiri. Bagi saya, Camus menjelma
Meursault dalam meneriakkan protesnya atas diberlakukannya hukuman mati. Ini
bukan anjuran, teriakan itu hanyalah salah satu sumber diskusi dalam memahami
penerapan hukuman mati. Kita punya hak untuk tidak sepakat dengan Camus.
Meursault menerimanya, dan untuk
pertama kalinya, ia memikirkan ibunya. Ia meyakini saat- ibunya meregang nyawa,
kebebasan datang menjemputnya untuk menghidupkan semuanya kembali dari awal.
Meursault juga punya keinginan terakhir sebagaimana lazimnya kita ketahui pinta
terpidana mati. Ironis, protes, ataukah sebentuk ejekan. Silakan mengartikan: “…Supaya semua tereguk, supaya aku merasa
tidak terlalu kesepian, aku hanya mengharapkan agar banyak penonton datang pada
hari pelaksanaan hukuman matiku dan agar mereka menyambutku dengan meneriakkan
cercaan-cercaan.” Ucapnya.
***
Pangkep-Makassar, 23 Juni 2014


Komentar