Si Cantik dari Eka
Ada empat mahasiswa dan satu siswa dalam perjalanan itu,
Sukman, Adi, Mahfud, dan Tini. Semuanya kuliah di Universitas Muslim
Indonesia (UMI). Dan, sayalah siswa yang nekat meninggalkan sekolah selama
sebulan. Perjalanan ini memang kami rancang dan dipersiapkan secara matang.
Kira-kira sebulan bergerilya mencari dana dan saban malam berkumpul guna
mengevaluasi dan mendiskusikan agenda.
Tujuan pertama, tentu saja kota Yogyakarta, kami memang
membaca banyak buku yang diproduksi dari ibu kota Jawa Tengah itu yang kemudian
membuat kami mengenal Mansour Fakih dan Roem Topatimasang. Keduanya pendiri
Insist. Itu salah satu agendanya, mengunjungi kantor Insist dan berjumpa dengan
kedua tokoh tersebut.
Karena kami menginap di pendopo Insist selama dua malam,
kami pun leluasa mengamati kerja orang-orang yang ada di sana. Termasuk
nongkrong membaca di toko buku yang terdapat di bagian depan kantor Insist.
Pada umumnya, buku-buku yang kami jumpai di situ tidak terlalu banyak tetapi
tidak pernah kami lihat di Makassar.
Di salah satu rak bersusun lima, misalnya, hanya diisi
sebuah buku. Sampulnya menggoda, seorang
perempuan sedikit menunduk seperti berusaha membuka kancing gaunnya. Atau bisa
pula dimaknai baru saja melepaskan gaunnya dan mengenakannya kembali. Saya lalu
meraih dan menatapnya dengan seksama. Oh, rupanya sebuah novel gubahan Eka Kurniawan, segerah buku itu saya simpan kembali.
Novel adalah sesuatu yang tak perlu dibaca, dan saya belum membaca riwayat sang
pembuatnya. Kesimpulanku ketika itu.
Saya hanya membaca buku teori perubahan
sosial sekelas Paulo Freire dan sejumlah buku ulasan Erich Fromm. Saya kapok membeli novel tebal, Bumi
Manusia Pram saja belum saya tuntaskan yang saya beli di tahun 2002. Meski
begitu, saya tertarik juga dengan sebuah news
letter bersampul merah maron. On/Off, nama media itu. Di dalamnya terdapat
ulasan Eka Kurniawan mengenai proses kreatifnya menuliskan novel.
Perjumpaan kembali yang tidak diduga.
Saya menemukan Si Cantik (Baca: Novel
Cantik Itu Luka) di toko buku samping stadion Andi
Mattalata, Makassar. Dejavu,
gambar sampulnya kembali menggoda. Dan, tak terasa saya telah membaca sebagian isinya. Niat awal
ingin membeli buku lain, tetapi kemudian novel gemuk itulah yang kubawa ke kasir untuk menukarnya dengan
sejumlah uang. Itulah awal mula saya kembali membaca novel setelah gagal menuntaskan Bumi
Manusia.
Pertanyaan awal yang mengganggu
usai novel ini saya tuntaskan: Begitu sakitkah sebuah keluarga di zaman kolonial, tepatnya ketika
rezim Jepang berkuasa
di negeri ini.
Dewi Ayu, tokoh utama dalam novel ini. Keturunan Belanda dan
memilih menjadi (atau dipaksa) melacur di rumah Mama Kalong. Tetapi, itu
boleh jadi sebentuk taktik,
protes, dan perlawanannya atas kondisi sosial yang ada. Hasilnya, Ia
dianugerahi empat orang anak perempuan
yang tak jelas dari lelaki mana yang menyimpan benih dalam rahimnya,
yang kemudian anak-anaknya itu melewati hari-hari yang tak kalah rumitnya.
Dewi Ayu benar, kecantikan itu muasal bencana. Cucunya,
Rengganis mengaku telah dihamili seekor anjing. Maman Gendeng, sang ayah,
kemudian mengamuk membunuh anjing-anjing di kota begitu buah hatinya dengan
Maya Dewi, anak ketiga Dewi Ayu, kabur bersama bayinya. Kejadian itu pula
membuat Ai, sepupunya, anak dari Shocando bersama Alamanda, putri pertama Dewi
Ayu, terkejut dan mati.
Adapun Krisan, anak dari Kamerad Kliwon dengan Adinda, putri
kedua Dewi Ayu. Dialah yang membunu sepupunya sendiri, Rengganis. Duka itu
masih ada, Maman Gandeng wafat dalam pencarian anaknya. Shocando lebih tragis
lagi, tewas tercabik karena dikeroyok kawanan anjing liar. Dan, Kamerad Kliwon
mati dalam sunyi, gantung diri.
Jadilah ketiga putri Dewi Ayu menjanda. Kemudian ia hamil
lagi dan melahirkan anak keempatnya. Semasa kehamilan, ia berdoa agar kelak
anaknya itu lahir dengan wajah buruk. Doanya terkabul, hidung jabang bayi itu
menghadap ke atas, hampir menyerupai hidung babi. Meski begitu, ia menamainya
Si Cantik.
Tetapi rupanya, derita belum berakhir. Setelah dewasa, Si
Cantik malah hamil sebelum menikah, dan itu dilakukan oleh sang pangerannya.
Tahukah Anda, siapa pangeran itu, tak lain anak kakaknya sendiri, Adinda. Ya,
Krisan yang melakukan perbuatan itu. Anak ini sendiri kemudian mati di tangan
seorang penggali kubur.
Saya bahagia telah membaca novel yang menurut kritikus,
memadukan gaya realis dan surealis dalam membangun cerita. Eka memang
memulainya dengan menceritakan kebangkitan Dewi Ayu dari dalam kuburnya setelah
25 tahun. Mungkin agak mirip dengan awal mula Metamorfosis, novel Frans Kafka.
Eka memang mengakui kehebatannya, ia sendiri menulis di laman blognya. “Gregor Samsa
terbangun dari satu mimpi buruk dan menemukan dirinya menjadi seekor kecoa
besar.” Adakah yang
lebih sempurna dari pembukaan cerita semacam itu? Tulis Eka.
Di sisi lain kita menemukan semangat Gabriel Garcia
Marquez dengan menciptakan kota Halimunda dan latar zaman kolonial yang mungkin
dipinjam dari Pramoedya Ananta Toer. Candu ketiga sastrawan itu tentulah tak
bisa dilepaskan oleh pengarang sesudahnya. Termasuk Eka, kita, dan Anda semua
yang tergugah oleh sebuah novel.
Ketika novel ini kemudian diterbitkan ulang Gramedia di
tahun 2004, saya sedikit kecewa dikarenakan sampulnya berubah. Ada kemiripan
dengan cover novel Paulo Coelho, Veronika
Memutuskan Mati. Kemudian berubah lagi setelah dicetak ulang di tahun 2012,
covernya malah mengaburkan konteks. Melihat sampulnya, asosiasi orang akan
menduga kalau cerita dibangun di sebuah kota metropolitan. Tetapi, itu urusan
penerbit dengan kalkulasi penjualannya. Dan, saya menolak membeli novel ini
sebagai hadiah kepada seorang kawan, hanya karena perubahan cover saja. Saya
senang dengan cover pertamanya, terbitan Jendela kerja sama Akademi Kebudayaan
Yogyakarta tahun 2002.
***
Pangkep-Makassar,
12 Desember 2013
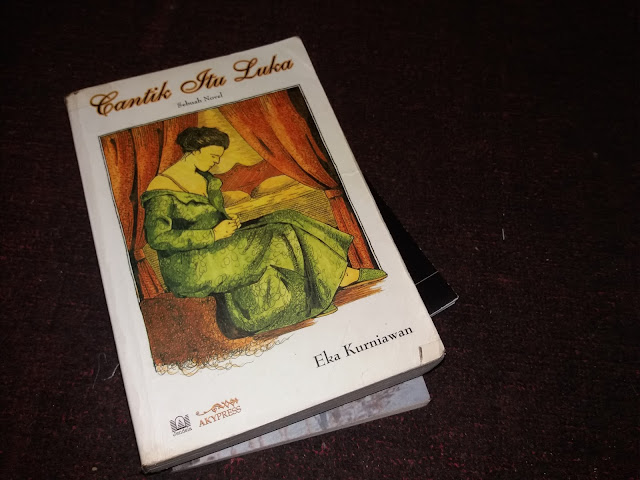


Komentar