Huruf Kecil Aan
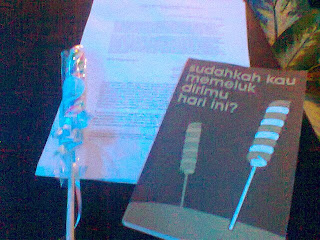 |
| Dok. Kamar Bawah |
Sudahkah Anda baca puisi hari ini? Saya
yakin belum. Sudahkah
Anda mengecek akun Facebok anda hari ini? Saya yakin selalu. Sudahkah Anda menulis puisi
hari ini? Saya yakin belum. Sudahkah
Anda mengirim pesan pendek hari ini? Saya yakin sudah puluhan atau bahkan
ratusan. Sudahkah
Anda membeli buku puisi hari ini? Saya yakin Anda belum punya rencana. Sudahkah Anda memesan makanan
cepat saji hari ini? Saya yakin Anda tak mau ketinggalan.
“Buku puisi telah menjadi korban diskriminasi di semua
toko buku di dunia,” ucap penyair, M
Aan Mansyur di
peluncuruan buku puisinya, Sudahkah Kau
Memeluk Dirimu Hari Ini di suatu malam di tahun 2011 di café Ininnawa di
jalan Sultan Hasanuddin, Makassar.
Secara pribadi lama sekali rasanya
baru bisa merdeka membaca puisi. Seingat saya, sudah lumayan banyak buku puisi
yang saya beli atau saya curi di perpustakaan kemudian saya baca sampai tuntas.
Dari lumayan banyak dan pembacaan tuntas itu, tak semuanya berakhir dengan
bahagia. Ukuran kebahagiaanya paling tidak mendorong saya untuk menulis tentang
buku itu. Ya, meski agak sulit disebut sebagai resensi. Karena dalam penyusunan
kata itu saya lebih senang menuliskan pendapat pribadi daripada memberikan
variabel tambahan seputar perbandingan, analisis sejarah, atau lain-lainnya
yang kira-kira sebagai ukuran untuk disebut sebagai resensi. Ataukah mencari lebih
detail perihal penyair tersebut. Menunggu buku-buku puisinya yang lain atau
mencari akun facebook dan blognya.
Menjadikan puisi sebagai salah satu
menu bacaan tentulah teramat sulit. Di sana sama sekali tidak ada kemerdekaan.
Mungkin karena pengaruh pelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang memberikan
pengertian mekanis terhadap sebuah puisi. Harus memiliki sekian bait, larik,
dan macam-macamnya. Saya ingat, ketika
menulis puisi di sekolah, yang kemudian dianggap bukan puisi oleh guru bahasa. Karena
puisi yang saya buat tidak memiliki bait yang jelas. Seolah karangan bebas
tanpa tujuan. Guru
bahasa menganggapnya tidak layak disebut puisi.
Dendam perlahan tumbuh, saya tidak
sepakat dengan penilaian guru bahasa. Namun, saya diam dan menolak
berdebat, karena saya anggap guru bahasa tersebut hanya menjalankan tugasnya
murni sebagai pengajar (bukan guru yang bisa membimbing). Hingga selesai masa sekolah, saya tak lagi menulis
puisi dalam ruang kelas
untuk memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam
diam, saya tetap mengumpulkan kata dalam secarik puisi di buku catatan harian.
Belakangan kuketahui kalau puisi yang saya buat dan tidak dianggap sebagai
puisi oleh guru bahasa, adalah puisi jenis prosa. Kerennya, puisi lirik. Setelahnya, saya berhenti
mendendam, namun saya iba. Apakah guru bahasa di sekolah saya dulu tidak
mengenal jenis puisi? Entahlah.
Dalam perjalanan selanjutnya, saya
mulai membaca puisi-puisi Chairil Anwar, Taufiq Ismail, dan Darmanto Jatman.
Yang membuat merdeka kemudian puisi-puisi pamfletnya Taufik Ismail dalam
antologi Tirani dan Benteng yang saya
curi di salah satu perpustakaan sekolah tinggi di Sorong, Papua Barat ketika merantau di
sana. Lalu saya lebih giat mencari puisi yang bergenre demikian. Lalu sampailah
pada puisi Wiji Thukul. Setelah mencari lagi, rasanya sulit menemukan pada penyair yang lain.
Saya menyimpulkan kalau puisi yang
demikian hadir seratus tahun sekali. Belakangan, saya menyadari jika anggapan keliru. Tetapi ini soal rasa (ideologi)
saja. Karena sastra bukanlah tujuan tunggal. Di dalamnya, orang-orangpun
berkelahi, dan di
dunia ini, saya kira Indonesialah sebagai satu-satunya negara yang pernah
menjadi arena dari perkelahian itu. Perseteruan dua kubu di masa lalu. Manikebu
dan Lekra adalah simbol sejarah yang akan terus diingat sebagai perjuangan
kesusastraan yang tak pernah bebas dari nilai.
Sekarang
Semua sudah bisa menulis puisi
berdasarkan kadar, rasa, dan celetuk tiba-tiba dari dalam hati. Lalu tak lama
sesudahnya, puisi atau yang dianggap puisi itu sudah bisa dibaca, dikomentari,
diperbincangkan melauli media yang sangat sederhana. Jejaring sosial. Sebuah
ruang maya yang belum seabad usianya, tapi membuat decak kagum umat manusia dan
selalu ingin terlibat dalam alurnya. Jalan ini memungkinkan setiap orang untuk
menuangkan apa saja. Tak perlu takut perihal kekurangan prisai atau
ketidaksiapan dalam berperang ketika ada yang mencoba mempertanyakannya. Toh,
ruang maya ini adalah tempat paling aman untuk berpura-pura.
Saya butuh waktu yang agak lama ketika
ingin memutuskan membeli sebuah buku kumpulan puisi. Karena harganya yang
terlampau mahal dengan wujudnya yang mungil dengan jumlah halaman tak cukup 200-an. Memang pertimbangan
teknis, karena saya mesti bermain judi dengan kemampuan keuangan yang tak jelas
masukannya. Semisal, mendapati buku puisi dengan harga Rp. 35.000,-. Saya mesti
mencari perbandingan dengan buku lainnya dengan harga serupa tapi jumlah
halamannya lebih banyak, yang biasanya
selalu berakhir dengan buku kumpulan cerpen. Hal ini saya anggap sebagai siasat
untuk memanjangkan
waktu membaca saja. Meskipun saya membuat luka dengan berpuasa atas buku puisi
yang telah saya korbankan hasil keputusan mekanis itu.
Salah satu korbannya, sebuah buku dari
penyair kelahiran Bone, Sulawesi Selatan yang sudah sering saya lihat ketika berkunjung di cafe
baca Bibliholic sekitar tahun 2004 silam. Judulnya sederhana dan jelas membuat
segudang tanya. Aku hendak Pindah Rumah. Demikian
judul antologi buku puisi itu. Saya menemukannya di salah satu toko buku di
Makassar.
Ketika meraihnya, berharap bisa membelinya lalu membuat
perencanaan untuk mendapatkan tanda tangan penyairnya. Tetapi itu gagal. Saya marah, dan membuat kesimpulan.
Mengapa buku tipis itu mahal. Terlintas pula rencana untuk mencurinya, namun
yang punya toko buku adalah seorang teman. Saya kecewa. Mungkin bukan pada
tempatnya. Tetapi itu
sungguh saya rasakan. Sesaat kemudian saya menghela nafas dan meyakinkan diri kalau
isi dompet terasa amat sukar keluar untuk melunasi buku itu di kasir. Karena
dengan uang yang sama saya bisa mendapatkan buku lain dengan jumlah halaman
lebih banyak. Lagi-lagi pertimbangan mekanis menguat. Celakanya lagi,
teman-teman saya yang rajin membaca tak pernah sekalipun menyentuh puisi. Jadi
peluang untuk meminjam buku puisi darinya otomatis tertutup. Keinginan terkecil
saya, saya bisa mempengaruhinya untuk membeli buku puisi itu. Tetapi, puisi
bagi teman-teman pembaca saya bukanlah sesuatu yang wajib. Sewajib bacaan Filsafat.
Saya yakin kalau kelak, saya bisa
membeli buku penyair itu lengkap dengan tanda tangannya pada waktu yang
bersamaan.
Jejaring Sosial
Saya baru menggunakan alamat email di tahun 2009, setahun kemudian baru
sepakat untuk membuat akun Facebook. Di akhir tahun 2010 saya membuat Blog
atas petunjuk seorang teman. Khususnya melalui akun Facebook, saya mulai mencari nama-nama yang tertinggal di masa
lalu. Perlahan ingatan itu tersambng kembali. Tentang keinginan yang batal
terwujud, dan hal lainnya yang saya kira penting untuk saat ini. Era ketika
begitu mudahnya membangun hubungan dengan orang-orang yang hendak dikenal.
Ya, pertimbangan mekanis saya sedikit
terbayarkan. Menyelami puisi-puisi yang sempat tertunda. Akhirnya saya bisa
sambung kembali melalui blog di mana M Aan Mansyur menyimpan arsip
puisinya di sana. Saya kurang tahu apakah puisi-puisi dalam antologi Aku hendak
Pindah Rumah juga ada dalam blog itu. Namun, keinginan
untuk membaca puisi dengan judul yang panjang-panjang itu sudah saya eja.
Sesekali pula saya dapatkan puisinya di harian Kompas.
Membaca satu judul puisi M Aan Mansyur
seolah menuntaskan sebuah catatan perjalanan panjang anak manusia. Tidak ada
kesimpulan sebagaimana yang diinginkan oleh sang pembuat sajak. Kita sepertinya menemukan
pengalaman komunal dalam puisi-puisi itu sembari berkata: “Ini sepotong kisah yang pernah saya alami, atau cerita ini adalah
impian saya.”
aku
hendak pindah rumah. segera. di suatu daerah, konon, ada
rumah akan dijual dengan harga murah. di sana, tidak ada larangan marah. tidak
ada perintah untuk mengurut dada. tidak ada tetangga yang hidup dengan mata
terkatup atau pintu dan telinga tertutup. (Aku hendak Pindah Rumah. Hal. 65)
Potongan puisi di atas dengan judul Aku hendak Pindah Rumah salah satu dari
penemuan pengalaman dan harapan itu. Pada dasarnya setiap orang menginginkan
petak kehidupan yang damai berdampingan dengan manusia-manusia lainnya di mana
rumah tak sekadar
sebagai pelindung dari panas dan hujan. Ataukah rumah bukan sebagai garis
pembatas atas masalah sosial yang dihadapi.
Menemukan diri dalam sejudul puisi M
Aan Mansyur tidak hanya berakhir pada realitas sosial. Ada banyak
perangkap-perangkap masa lalu dan situasi faktual yang dihadapi anak-anak muda
dalam proses pencarian bentuk pengungkapan
hati anak manusia. Wilayah ini sesungguhnya sangatlah naif, tetapi penyusunan kata yang
digunakan M Aan
Mansyur membuat kita sulit berpaling. Kita selalu saja tertantang untuk
terlibat dalam eksperimen ini. yang dalam warisan sejarah persajakan di negeri
ini, itu bisa dikatakan sebagai suatu yang baru. Masih sangat sedikit penyair
yang memproklamirkan puisinya dengan kata sederhana namun sekaligus membuat
kesimpulan dan ingin segera berucap: “Ya,
kalimat itulah yang selalu ingin saya ucapkan.”
pada
sebait ini,
aku
putuskan menjadi sapu
bagi
diriku yang sampah
(Sapu. Hal. 116)
Puisi pendek ini sungguhlah menerjemahkan
definisi kegelisahan-kegelisan dalam diri manusia yang memang tempatnya lupa,
khilaf, dan dosa sekaligus atas sesuatu perbuatan yang dianggap keliru. Jika
meyakini kalau selalu saja ada rasa yang bertarung dalam diri manusia. Menjadi
baik atu sebaliknya. Dan, disitulah
letak perjuangannya.
Mengeja puisi-puisi M Aan Mansyur saya kira mengajak
kita bermain dengan pristiwa masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ia
hanya mengantar kita ke ujung jalan yang penuh cabang. Bahwa apakah soal yang
selalu kita ajukan diketemukan di ujung jalan itu ataukah kita masih harus
menemukannya dengan ragam cabang jalan yang sudah ditunjukkan dalam sejudul
puisi. Entahlah, kita berhak menafsirkannya sebagai kebenaran berdasarkan kesadaran
kita masing-masing. Sebagaimana ditulisnya sendiri.
“Saya
tidak menyukai kebenaran disampaikan seperti khotbah Jum’at. Saya pikir setiap
orang punya kekuasaan dalam menafsir kebenarannya masing-masing.” (Hal.vi).
Sesederhana itulah penyair kelahiran 14
Januari 1982 ini menyebarkan pluralisme berfikir bagi pembaca puisi-puisinya. Pada
suatu kesempatan bedah buku puisinya di Makassar. M Aan Mansyur mengungkapkan kalau
puisinya merupakan rangkuman-rangkuman pertanyaan atas apa yang telah
diamatinya, dirasakan, atau bahkan bagian perjalanan hidupnya sendiri. Proses
kreatifnya perihal puisi tumbuh atas keterbatasan-keterbatasan yang mendekapnya
di masa lalu. Jujur, ia menuliskan:
“Waktu kecil saya terobsesi ingin
menjadi pemain musik dan pelukis. Saya menganggap musik dan lukisan bisa
membuat hidup yang rumit, seperti hidup ibu saya, menjadi lebih tenang. Tetapi
kata ibu, “Kamu bisa melakukan keduanya sekaligus dengan menulis.” Kata-kata,
katanya, adalah alat yang bisa digunakan untuk menciptakan musik, lukisan, dan
bahkan tarian. Saya tahu, dia mengatakan itu karena tak mampu membelikan alat
musik dan perlengkapan melukis untuk saya.setelah berkali-kali menulis puisi,
saya pikir kata-kata ibu saya itu benar adanya.” (Hal. v)
Mungkin itupula sebabnya, pembaca
pertama yang membaca puisinya adalah ibunya sendiri yang ia kirimkan melalui
pesan pendek. Pertanyaan seketika muncul, sebegitu subtilkah hubungan penyair yang sudah memproklamirkan
5 judul kumpulan puisi plus sebuah novel ini. Hanya M Aan Mansyur sendirilah yang
bisa menakarnya. Sebagai pembaca yang kita tahu dari tulisannya, sebatas
menduganya. Namun itu bukan soal yang mesti diperbincangkan khalayak pembaca.
Yang kita tahu, puisi M Aan
Mansyur telah berhasil merekam sepotong laku kita dalam sejudul puisi. Serta
pembangunan sebuah ruang bernama puisi sebagai perekam narasi, data-data, dan
protes sekaligus.
Huruf Kecil
Apa yang paling mudah diingat atas
puisi M Aan Mansyur. Selain penggunaan ragam simbol, bahasa sederhana, dan
judul yang panjang-panjang. Apalagi kalau bukan huruf kecil. Judul blognya juga
demikian. kita tidak akan menemukan huruf kapital di awal kalimat ataupun
setelah tanda baca titik. Mungkin ini sebentuk simbol juga.
Melaui buku puisinya, Sudahkah Kau Memeluk Dirimu Hari Ini yang merupakan
buku pertamanya yang saya beli dan langsung mendapat tanda tangan pada saat
bersamaan (suatu
keinginan tahun 2004 silam). Meski itu bukan perjumpaan yang pertama. Tahun
2011 lalu ketika pertama kali dilaksanakan Makassar International Writer
Festival (MIWF) saya sempat foto bersama di Museum Balai Kota.
Kembali soal huruf kecil.
Penggunaannya dengan melanggar tata baku bahasa meski sebenarnya dalam dunia
puisi hal itu bukanlah hal yang haram. Namun saya mendapati sebuah cerpen di
blognya yang seluruhnya menggunakan huruf kecil. Bahkan pada buku Sudahkah Kau Memeluk Dirimu Hari Ini
yang seluruh kutipan puisi dan catatan dalam telaah ini bersumber dari buku
tersebut, yang saya kira merupakan buku rangkuman puisi-puisi M Aan Mansyur dari buku kumpulan
puisi yang sebelumnya sudah terbit? Pada halaman keterangan data teknis buku
ini pun semuanya menggunakan huruf kecil.
Ya, pada situasi tertentu, M Aan Mansyur telah
mengganggu kita. Mengganggu kemapanan dalam pola pikir kita perihal penggunaan
huruf kecil dalam karya tulis. Tetapi
sekaligus mengajak kita untuk merancang perlawanan dalam kemapanan-kemapanan
yang sejauh ini telah mengurung kita.
Kalau saja puisi-puisi M Aan Mansyur
diperiksa oleh guru bahasa saya ketika sekolah dahulu. Maka puisinya akan dianggap
sebagai penghinaan terhadap Tuhan. Karena yang lazim, penulisan kata Tuhan atau
yang merujuk terhadapnya dalam rimba teks di manapun posisinya dan bentuknya,
haruslah diawali dengan huruf kapital. Semisal: Kepada-Nya. Akhiran ‘Nya’
adalah pengungkapan akan Tuhan. Namun dalam sejudul puisi M Aan Mansyur yang mengunakan
kata ‘Tuhan’. Rambu itu tak berlaku. Ada beberapa judul puisi yang saya kira
kembali merekam tata laku, harapan, dejavu, dan hal-hal lainnya yang bisa saja
merujuk pada rasa dalam diri kita di dalam puisi itu. Mari kita simak:
Pertama puisi yang berjudul Puisi tentang Doa yang Terbata-bata.
Dalam rekam jejak sebuah keluarga, maka posisi bapak selalu saja sebagai kepala
keluarga. Sebait dalam puisi ini hal itu sangat jelas. Sang anak menggambarkan
kalau bapaknya sungguh tak mau keluarganya terperosok ke dalam kekurangan atau
bahasa sosialnya. Kemiskinan. Sang bapak ingin menjadikan dunia sebagai tabungan
keluarga untuk masa depan sang anak. Sebentuk metafora yang digunakaan M Aan Mansyur sebagai jalan
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi. Hal ini terjelaskan dengan
tampikan sang anak yang berdoa. Tepatnya mencoba “memerintah” Tuhan.
“tuhan,
mauka kau mengatakan kepada bapak
agar dia
berhenti bercita-cita seperti anak kecil?
dia
ingin dunia dan isinya menjadi tabungan keluarga.
katanya
untuk masa depan aku, padahal aku tak
mau
menanggung dosa itu. tuhan, tolonglah aku!
(Hal. 23)
Apakah perihal esensi doa ini luput
dari M Aan Mansyur. Ataukah ia hendak merekam alam pikiran anak-anak di mana
kita dahulu
berbuat demikian. Kemungkinan lainnya, M Aan Mansyur mengajak kita untuk
memasuki ruang bernama institusi. Termasuk sebuah keluarga, sekolah, dan taman
pengajian. Bahwa ada yang lemah dalam pengenalan hubungan anak dengan Tuhan
melalui institusi tersebut. Sehingga kepolosan anak yang berdoa, seolah bisa
‘memerintah’ Tuhan.
Saya ingin mengutip Ali Syariati perihal doa.
Bahwa doa yang sejauh ini kita panjatkan sesungguhnya mengajak Tuhan turun dari
aras-Nya. Padahal sesunguhnya doa itu sebuah munajat yang memuji asmah-Nya. Doa
adalah eleksir cinta antara manusia dengan zat yang kita kenal dengan Tuhan.
Tetapi
ini puisi. Karena saya kira puisi itu juga doa. Atau kita simpulkanlah puisi
ini adalah kesaksian seorang anak yang melihat kejanggalan dalam perencanaan
usaha sang bapaknya untuk membahagiakan dirinya. Dan, sang anak menjelma puisi yang
juga merupakan realitas yang bertanggung jawab pada hidup yang mungkin dahulu menjadi sangsi bagi sang
bapak.
entah
mengapa selalu aku bayangkan aku
bapak
sedang diam-diam menangis membaca
puisi
ini, doa anak yang terbata-bata ini.
terimah
kasih, tuhan,kau jadikan anakku puisi.
Tuhan yang lain
saya temukan pada puisi Kata Peramal
aku
baru saja menemui seorang peramal.
disarankannya
kepadaku beberapa hal.
(Hal. 63)
Demikian bait pembuka puisi ini. Empat
bait setelahnya adalah hal-hal yang disarankan peramal yang terbagi ke dalam
dua kategori. Perintah dan pengingatan. Kemudian ditutup dengan bait di mana
Tuhan menjadi menyesal. Sekali lagi, sebuah metafora.
tetapi
jika kau tak mampu melakukannya,
apapun
yang terjadi, jangan mau menangis.
sebab
air mata itu bahkan tuhan pun
terus
menyesal telah menciptakannya.
Bahkan bagi pembaca yang
mengulang-ngulang teks pada bait terakhir ini. Akan berhenti seketika lalu
mengungkapkan: “Adakah ciptaan Tuhan yang tak berguna.” Penjelasan dalam sebuah surah
Alquran (Ar-Rahman). Fabiayyi Ala I Robbikuma Tukazziban. Nikmat
Tuhan yang manakah yang kau ingkari. Hemat saya, M Aan Mansyur melalui sejudul
puisi kembali menawarkan sebentuk penangkapan eksistensi yang terkadang kita
sulit luruskan perihal asal muasal dari gejolak sosial yang tengah dihadapi.
Tuhan dengan huruf kecil kali ini betul-betul Tuhan yang kita definisikan.
Tiga puisi lainnya. Pohon-pohon
tidak Berdaun,
Apakah Puisi ini Membenci (Puisi) Hujan,
dan Tiga Catatan yang Aku Tulis di Kotamu
dan Satu di Pesawat Perihal Catatanmu.Tuhan hadir sebagai harapan dan Tuhan
disebut sebagai pengingat akan kelalaian.
di
tengah-tengah begini tahun
langit
adalah tuhan bagi hutan
(Pohon-pohon tidak Berdaun. Hal. 64)
sebab
bahkan sekiranya bertahun-tahun tuhan
mengguyur
tubuh kita ini dengan hutan hujan,
panasnya
kata-kata di koran yang melukai kita
tak akan
mampu sembuh sebagaimana semula
(Apakah Puisi ini Membenci (Puisi)
Hujan. Hal 132)
sejumlah
anak kecil menangis, orang-orang tua panik
dan
berpegangan pada doa, pada lengan-lengan tuhan
(Tiga Catatan yang Aku Tulis di Kotamu
dan Satu di Pesawat Perihal Catatanmu. Hal. 159)
Demikianlah M Aan Mansyur merekam realitas
dalam puisinya, sekaligus menantang kita untuk berfikir, merenung, dan mulai
mempertanyakan sesuatu. Kata-kata mengalir menolak bentuk mekanis dan kurungan
sempit sebuah definisi baku. Yang jelas kata sudah tersusun untuk menjelaskan
dirinya sendiri. Sebagaimana penggunaan huruf kecil untuk menulis Tuhan. Kita
pun semestinya bertanya. Apakah Tuhan terpengaruh dengan huruf kecil itu. Mari
renungkan.
Saya berterimah kasih atas
puisi-puisi yang ditulis M Aan
Mansyur. Beberapa diantaranya mengundang saya untuk mengembangkannya ke dalam
karya tulis lainnya. Sejudul puisi M Aan Mansyur tak hanya merekam kita
dalam suatu ketika, tetapi
juga nafas tambahan dari kelelahan merampungkan sebuah rencana kerja.
Sebagai penutup,
saya ingin mengutip sejudul puisi lagi. Yang saya kira merekam harapan saya (kita) di sana.
aku
menulis puisi sebab waktu kanak-kanak aku ingin menjadi
seorang
astronot-dan tidak mau guru dan teman-temanku
tertawa
sekali lagi karena ibuku janda penjual tomat. aku
menulis
puisi agar mereka tahu anak penjual tomat juga boleh
menyimpan
cita-citanya di bulan, di langit, atau di tempat yang
yang
jauh lebih tinggi.
(Kepada Cucu Seorang yang Menolak
Aku Menjadi Menantu. Hal. 139)
***
Makassar, 13 Juli 2012
Versi pendek dimuat di Rubrik Apresiasi Fajar, 29
Juli 2012


Komentar